Di balik gegap gempita media sosial dan hiruk-pikuk pemberitaan infotainment, kasus hukum yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani menjadi sorotan publik dengan segala pro dan kontranya.
Namun, lebih dari sekadar drama hukum selebriti, kasus ini menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana masyarakat menilai sebuah peristiwa. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam kesalahan berpikir yang disebut ad hominem.
Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “menyerang orangnya, bukan argumennya.” Dalam dunia logika, ad hominem adalah salah satu logical fallacy atau sesat pikir yang paling umum, tetapi sekaligus berbahaya.
Kesalahan berpikir ad hominem terjadi ketika seseorang menolak argumen, fakta, atau pendapat hanya karena tidak menyukai siapa yang menyampaikannya.
Dalam kasus Nikita Mirzani, publik kerap menilai persoalan hukum bukan berdasarkan substansi perkara, melainkan berdasarkan rekam jejak, sikap, atau citra dirinya yang selama ini dikenal penuh kontroversi.
Komentar seperti “wajar saja dia kena kasus, kan memang mulutnya kasar” atau “artis sensasional seperti itu pantas dihukum” adalah contoh nyata dari serangan ad hominem. Padahal, yang seharusnya menjadi fokus adalah apakah benar ada pelanggaran hukum yang dilakukan, bukan bagaimana perilaku atau gaya hidup pribadi terdakwa di masa lalu.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana opini publik di era digital sangat mudah dibentuk oleh narasi personal. Media sosial, dengan algoritmanya yang cepat menyebarkan sensasi, ikut memperparah situasi. Alih-alih mendiskusikan pasal-pasal yang relevan atau fakta persidangan, masyarakat lebih sibuk memperdebatkan moralitas pribadi Nikita Mirzani.
Padahal, dalam hukum, asas yang berlaku adalah praduga tak bersalah setiap orang berhak diperlakukan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ad hominem membuat asas ini terdistorsi karena publik lebih dulu “menghukum” dengan stigma.
Mengapa ad hominem berbahaya? Pertama, ia merusak proses pencarian kebenaran. Hukum adalah instrumen rasional yang seharusnya bekerja berdasarkan bukti dan aturan, bukan berdasarkan simpati atau antipati terhadap individu. Kedua, ad hominem memperkuat budaya persekusi digital. Di era media sosial, komentar yang menyerang pribadi lebih cepat viral dibandingkan analisis hukum yang mendalam.
Hal ini berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum, karena opini publik bisa memberi tekanan yang tidak sehat terhadap jalannya proses hukum.
Kasus Nikita Mirzani hanyalah satu contoh dari sekian banyak perkara yang terdistorsi oleh fallacy ini. Jika hari ini ad hominem menimpa seorang selebriti, bukan tidak mungkin besok ia menimpa masyarakat biasa yang berhadapan dengan hukum.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis dan menyadari jebakan logika ini. Kita bisa tidak menyukai gaya bicara atau sikap seseorang, tetapi ketika berbicara tentang hukum, yang harus dikedepankan adalah fakta, bukti, dan aturan.
Artikel ini bukanlah pembelaan terhadap Nikita Mirzani, juga bukan penghakiman terhadap dirinya. Ini adalah ajakan agar kita berhati-hati dalam menilai, terutama di era digital ketika narasi sering kali lebih kuat daripada realitas.
Ad hominem mungkin terlihat sepele, tetapi ia adalah racun halus yang bisa merusak nalar publik, mengaburkan fakta, dan pada akhirnya menghambat tegaknya keadilan. Jika ingin masyarakat hukum yang sehat, maka kita harus berani melawan godaan untuk menilai perkara dari siapa yang berbicara, dan kembali fokus pada apa yang sebenarnya dipersoalkan.

Apa Itu Fallacy Ad Hominem?
Dalam dunia logika dan hukum, ad hominem dikenal sebagai salah satu bentuk kesesatan berpikir (logical fallacy) yang paling sering muncul, baik dalam perdebatan akademik, politik, maupun kasus hukum yang disorot publik. Secara sederhana, ad hominem terjadi ketika seseorang tidak membantah substansi argumen, data, atau fakta hukum yang diajukan, melainkan justru menyerang aspek pribadi dari pihak yang berbicara. Aspek tersebut bisa berupa karakter, gaya hidup, status sosial, riwayat hidup, bahkan isu-isu pribadi yang tidak relevan dengan pokok perkara.
Kesalahan berpikir ini menyesatkan karena mengalihkan fokus dari inti persoalan hukum ke ranah yang tidak ada kaitannya dengan bukti atau norma hukum yang sedang dipersoalkan. Alih-alih menguji validitas argumen, ad hominem menciptakan distraksi emosional yang membuat audiens cenderung menilai berdasarkan prasangka pribadi.
Dalam konteks hukum, hal ini berbahaya karena dapat menggiring opini publik untuk menyalahkan seseorang bukan karena kesalahan yuridis yang terbukti, melainkan karena citra atau reputasi buruk yang melekat padanya.
Contoh sederhananya adalah pernyataan seperti: “Dia pasti bersalah karena selama ini suka cari sensasi dan masalah.” Kalimat semacam ini jelas tidak berbasis pada bukti hukum, melainkan pada stigma personal.
Padahal, sistem hukum modern menuntut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti melalui putusan pengadilan yang sah. Sayangnya, ad hominem kerap mengaburkan asas ini, apalagi di era digital ketika opini publik lebih mudah dibentuk melalui media sosial dan pemberitaan sensasional.
Jenis-jenis ad hominem juga beragam. Pertama, abusive ad hominem, yaitu serangan langsung terhadap kepribadian seseorang, misalnya dengan kata-kata kasar atau merendahkan.
Kedua, circumstantial ad hominem, yaitu upaya melemahkan argumen dengan menunjukkan latar belakang atau kepentingan pribadi lawan debat, seolah-olah argumennya tidak sah hanya karena ia memiliki motivasi tertentu.
Ketiga, tu quoque ad hominem, atau dikenal dengan “serangan balik,” di mana seseorang dianggap tidak layak berbicara karena ia sendiri pernah melakukan hal yang sama. Semua bentuk ini, meskipun berbeda, memiliki kesamaan: menghindari substansi dan menyerang individu.
Dalam kasus-kasus hukum, ad hominem sering muncul ketika publik atau media membicarakan sosok terdakwa atau pihak yang terlibat. Alih-alih menyoroti pasal yang dilanggar, bukti yang diajukan, atau proses peradilan, diskusi justru bergeser ke arah kehidupan pribadi.
Misalnya, ketika seorang artis tersandung kasus hukum, komentar yang muncul di media sosial lebih banyak menyoroti gaya hidup, sikap, atau kontroversinya di masa lalu. Padahal, aspek tersebut tidak relevan dalam menentukan apakah ia benar-benar bersalah dalam kasus yang sedang dihadapi.
Bahaya ad hominem bukan hanya soal bias, tetapi juga soal keadilan. Jika masyarakat terus-menerus menilai berdasarkan reputasi personal, maka ada risiko bahwa proses hukum ikut dipengaruhi oleh tekanan opini publik.
Aparat penegak hukum bisa saja terjebak untuk “menghukum” bukan karena bukti, melainkan karena citra buruk terdakwa di mata masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan hukum.
Kesadaran akan bahaya ad hominem penting untuk membangun budaya hukum yang sehat. Masyarakat harus belajar memisahkan antara siapa yang berbicara dengan apa yang dibicarakan.
Tidak menyukai pribadi seseorang bukan berarti argumennya otomatis salah, begitu juga sebaliknya. Dalam hukum, kebenaran hanya bisa ditegakkan melalui fakta, bukti, dan norma yang berlaku, bukan melalui serangan pribadi yang memancing emosi.
Dengan demikian, memahami dan menghindari ad hominem bukan hanya latihan logika, melainkan juga komitmen moral untuk menjaga keadilan. Di era digital, ketika narasi dapat membentuk opini lebih cepat daripada fakta, kesadaran ini menjadi semakin mendesak. Jika kita ingin sistem hukum yang adil dan masyarakat yang rasional, maka kita harus berani melawan jebakan ad hominem dan kembali berpegang pada bukti serta argumentasi yang sahih.

Kasus Nikita Mirzani: Fakta atau Framing?
Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bermula pada November 2024, ketika Nikita mengunggah ulasan negatif terhadap produk skincare milik Reza di akun TikTok miliknya. Merasa dirugikan secara reputasi, Reza kemudian menghubungi asisten pribadi Nikita, Mail Syahputra untuk menyampaikan keberatan.
Namun, dari komunikasi tersebut, Reza justru merasa diancam akan dibongkar di media sosial jika tidak memberikan uang dan atas dasar itu pada Desember 2024 Reza melaporkan Nikita ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian ditaksir mencapai Rp4 miliar.
Penyelidikan berjalan hingga awal 2025 dan pada bulan Maret Nikita resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan intensif, persidangan pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Juli 2025.
Saat itu, suasana sempat ricuh karena Nikita menolak mengenakan rompi tahanan dan menunjukkan penolakan terhadap perlakuan jaksa saat pihak jaksa dan hakim menolak atas pengajuan pemutaran flashdisk yang berisikan bukti bahwa Dr. Reza Gladis menyogok pihak hakim dan jaksa.
Nikita Mirzani berusaha untuk membuktikan bahwa pengadilan sudah tidak lagi netral
Namun Aksinya itu menuai sorotan publik dan memperkuat opini sebagian pihak bahwa ia tidak kooperatif, meskipun secara hukum ia masih berstatus sebagai terdakwa dan memiliki hak atas pembelaan.

Di luar ruang sidang, komentar dari publik dan figur media seperti Kiki The Potters semakin memperkeruh suasana.
Alih-alih membahas fakta hukum, sebagian besar komentar justru berisi serangan personal ad hominem yang merujuk pada karakter Nikita, gaya hidupnya, dan riwayat konfliknya di masa lalu dan anyak yang sudah menjatuhkan “vonis sosial” jauh sebelum hakim memutuskan perkara.
Hal ini mencerminkan bagaimana opini publik, yang dipenuhi bias emosional, bisa mengganggu objektivitas proses peradilan. Proses hukum masih berjalan, bukti masih diuji, pembelaan masih berlangsung. Namun di luar ruang sidang, publik seolah sudah memiliki vonis sendiri. Banyak komentar yang berbunyi:
- “Pantas saja masuk penjara, kelakuannya memang begitu dari dulu.”
- “Makanya jangan terlalu banyak ngomong, kan jadi kena karma.”
- Siapa suruh sok berani, sekarang tinggal nangis-nangis.”
Kalimat-kalimat ini tidak berbicara tentang alat bukti, pasal hukum, atau asas praduga tak bersalah. Ini murni serangan personal terhadap figur Nikita. Inilah ad hominem dalam bentuk yang paling vulgar.
Padahal, hukum tidak boleh bekerja berdasarkan siapa pelakunya, melainkan apa yang dilakukannya. Seperti yang ditegaskan oleh Prof. Latif Tile dalam jurnalnya Fallacies in Legal Reasoning (2024), kekeliruan semacam ini bukan hanya merusak nalar, tetapi juga bisa menggiring opini publik menjauh dari kebenaran hukum yang objektif.

Mengapa Ad Hominem Menyesatkan?
Fallacy ad hominem begitu mudah menyusup dalam diskursus publik karena ia bermain pada emosi, stereotip, dan citra seseorang. Ketika seseorang sudah dikenal “kontroversial”, publik cenderung langsung mengaitkan reputasi itu dengan kesalahan, bahkan sebelum ada bukti nyata yang disajikan. Logika ini berbahaya karena mengalihkan perhatian dari substansi perkara menuju aspek personal yang sama sekali tidak relevan. Akibatnya, masyarakat lebih sibuk menilai karakter ketimbang menguji argumen atau fakta hukum yang sebenarnya.
Sekarang bayangkan jika pola ini menimpa orang biasa, yang tidak memiliki panggung besar untuk membela diri. Di titik itu, penghakiman massa berubah dari sekadar tontonan menjadi bencana moral. Kehidupan seseorang bisa hancur hanya karena prasangka yang dipelihara oleh opini publik, bukan berdasarkan kebenaran.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ad hominem bukan sekadar soal kasus Nikita Mirzani atau figur populer lainnya. Lebih jauh, ini adalah cermin tentang bagaimana kita berpikir, bersikap, dan membentuk opini bersama di era digital. Jika nalar dikuasai oleh emosi dan serangan personal, maka keadilan yang objektif akan sulit tercapai, dan siapa pun berpotensi menjadi korban berikutnya.
Kekuasaan Kata dan Luka yang Menganga
Komentar Kiki The Potters yang menyebut Nikita Mirzani “siap-siap jadi nenek gayung di penjara” merupakan contoh nyata fallacy ad hominem. Alih-alih menyoroti fakta hukum, komentar tersebut justru menyerang aspek pribadi seperti status, usia, dan gaya hidup.
Serangan seperti ini adalah bentuk pengalihan dari substansi ke simbol, yang membuat publik terjebak dalam persepsi, bukan realitas hukum. Dengan begitu, ruang diskusi yang seharusnya membedah bukti dan norma berubah menjadi panggung ejekan.
Komentar semacam itu memang tampak lucu bagi sebagian orang, tetapi sesungguhnya berbahaya karena mengajak publik untuk ikut tertawa, bukan berpikir. Di balik candaan, ada dampak serius: harga diri seseorang direndahkan, stigma sosial diperkuat, bahkan objektivitas hukum bisa terdistorsi.
Padahal yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar citra seorang artis, tetapi juga kehidupan pribadi, masa depan anak-anaknya, serta kredibilitas sistem hukum itu sendiri. Ad hominem seperti ini menunjukkan betapa mudahnya keadilan dipelintir oleh narasi personal yang tidak relevan, dan betapa pentingnya kita belajar memilah argumen agar tidak terjebak dalam jebakan logika yang menyesatkan.
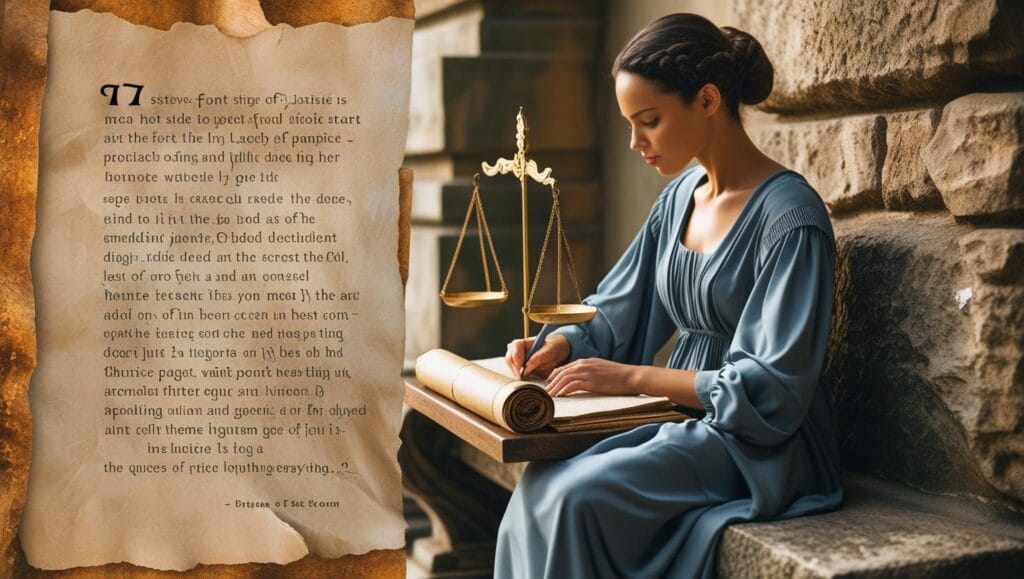
Ketika Emosi Mengalahkan Etika
Mengapa ad hominem begitu digemari? Karena ia langsung menyentuh emosi. Serangan terhadap pribadi terasa lebih memuaskan secara instan dibandingkan membedah argumen atau menelaah bukti. Dalam ruang digital yang penuh dengan opini cepat saji, komentar yang tajam dan sarkastik sering kali terasa lebih “mengena” dibandingkan penjelasan hukum yang objektif.
Dalam kasus Nikita Mirzani, gejala ini terlihat jelas. Banyak orang sudah mengambil kesimpulan sebelum memahami duduk perkara secara utuh. Kronologi diabaikan, konteks dilompati. Cukup satu potongan video atau satu komentar sarkastik di media sosial, publik merasa punya cukup alasan untuk menghakimi.
Padahal, yang mereka hakimi bukanlah tindakan atau bukti, melainkan karakter, masa lalu, dan citra personal yang dibangun media. Ad hominem menjadi alat yang cepat dan memuaskan, tapi sekaligus berbahaya. Ia mengaburkan batas antara opini dan keadilan, antara emosi dan pertimbangan hukum.
Penutup: Nikita Hanya Salah Satu Contoh
Kasus Nikita Mirzani hanyalah salah satu contoh yang mencolok dari betapa rentannya ruang publik kita terhadap jebakan ad hominem. Serangan personal, komentar sarkastik, hingga penghakiman massa sering kali menjadi “bumbu” dalam setiap isu yang muncul di media sosial. Padahal, dalam konteks hukum maupun logika, pola pikir seperti ini jelas menyesatkan.
Alih-alih membahas substansi perkara, publik justru lebih tertarik menyerang pribadi pelaku atau pihak yang sedang disorot. Ironisnya, perilaku ini tidak hanya terjadi pada artis atau figur publik, tetapi juga meluas ke ranah politik, aktivisme, bahkan kasus korban kekerasan.
Kita pernah menyaksikan bagaimana seorang tokoh politik tidak dinilai dari kebijakan atau rekam jejak kinerjanya, melainkan dari kehidupan pribadinya yang kemudian dijadikan bahan serangan. Aktivis yang menyuarakan keadilan pun tak luput dari stigma, mulai dari dicap sebagai provokator hingga dituduh memiliki motif tersembunyi.
Bahkan korban kekerasan sekalipun sering kali disalahkan dengan narasi “pasti ada salahnya juga,” yang merupakan bentuk paling kejam dari ad hominem. Semua ini mencerminkan satu hal: bahwa sebagai masyarakat, kita masih belajar berpikir secara adil dan rasional.
Mengapa fenomena ini berbahaya? Karena ia melahirkan budaya penghakiman tanpa bukti yang sahih. Ad hominem mengalihkan fokus dari substansi ke permukaan, dari fakta ke gosip, dari bukti hukum ke reputasi pribadi.
Dalam dunia hukum, prinsip praduga tak bersalah seharusnya menjadi benteng utama. Namun, di ruang publik digital, prinsip ini kerap runtuh oleh derasnya opini yang dibangun berdasarkan prasangka. Akibatnya, orang bisa “dihukum” oleh masyarakat jauh sebelum pengadilan mengeluarkan putusan.
Maka, kasus Nikita Mirzani dan kasus-kasus serupa seharusnya tidak kita lihat hanya sebagai tontonan atau bahan hiburan. Ada pelajaran besar yang perlu dipetik: pentingnya mengedepankan berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi.
Berpikir kritis berarti menilai argumen berdasarkan data, bukti, dan logika, bukan karena siapa yang mengatakannya atau bagaimana reputasi orang itu di mata publik. Dengan cara ini, kita menjaga agar nalar tetap berdiri di atas fakta, bukan runtuh oleh emosi.
Sayangnya, ad hominem begitu menggoda karena ia cepat, singkat, dan memuaskan kebutuhan emosional untuk menjatuhkan orang lain. Komentar sarkastik terasa lebih menghibur ketimbang analisis panjang berbasis hukum.
Namun, jika pola ini terus dibiarkan, maka keadilan akan menjadi korban pertama. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menjadi korban selanjutnya, karena siapa pun bisa diserang karakternya, siapa pun bisa dihancurkan reputasinya, tanpa kesempatan membela diri.
Oleh karena itu, mari jadikan fenomena ad hominem ini sebagai pengingat bersama. Senjata terbaik dalam menjaga keadilan bukanlah serangan personal atau komentar pedas, melainkan kekuatan berpikir kritis. Dengan nalar yang sehat, kita bisa menilai persoalan apa adanya, bukan berdasarkan siapa yang terlibat.
Dengan kesadaran kolektif semacam ini, masyarakat tidak hanya terhindar dari jebakan logika sesat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih adil dan beradab. Sebab, ketika ad hominem dibiarkan mendominasi, kita semua sesungguhnya sedang menyiapkan panggung bagi ketidakadilan berikutnya dan bisa jadi, korban selanjutnya adalah kita sendiri.
Baca artikel lainnya
3 Prinsip Islamicoin Halal yang Wajib Diketahui: Rahasia Cara Kerja Islamicoin!
Panduan Lengkap Pajak Hibah dan Waris (2025): Lebih Hemat Lewat Mana?
Hukum Hibah dan Waris dalam Islam: 6 Pertanyaan Penting yang Paling Sering Ditanyakan
Jejak Digital Tidak Pernah Hilang: 5 Kategori Konten Oversharing yang Berisiko
Rangkaian Demo DPR 25-31 Agustus 2025 Memanas Hebat
Sumber Referensi:
Nikita Mirzani Merasa Dikriminalisasi, Sudah Lima Bulan Tak Bisa Merawat Ketiga Anaknya
dr. Reza Gladys Cuek Dengan Stigma Planga-Plongo, Akui Tidak Terpancing Saat Sidang Tapi…
